Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
Oleh: Sugiono MP
Sastrapuna.com-Terharu mencermati status Muklis Puna berjudul Bagaimana Sih Puisi Sebenarnya? Kenapa? Dalam tiga hari mengumpulkan 240 likes (3-6/8/18). Itu berarti terapresiasi.
Meski penyair-esais Eko Windarto (yang mendekotomi sastra serius dan sastra hiburan) pernah menyatakan jumlah penanggap literasi gawai tidak sertamerta menentukan kadar tulisan, tapi setidaknya ada indikasi azas manfaat pada postingan yang dibaca banyak orang. Tentu saja hal itu tidak menjamin kualitasnya.
Postingan saya pada 2017 pernah mendapat likes 400 lebih di dua laman (Beranda dan Majalah Sastra Maya) bukan karena kualitas sastranya, melainkan oleh sebab publik pemula merasa mendapat guidance dari tulisan tersebut.
Meski judul status Muklis tersebut menyebut puisi, namun yang dimaksud adalah puisi di laman gawai. Menurut sastrawan Sosiawan Leak, peta sastra Indonesia dewasa ini terbagi dalam tiga segmen. Yakni sastra buku (dari penerbit major dan indie), sastra komunitas (lokal, nasional, Asia Tenggara) dan sastra internet. Yang terakhir itu, “Sejatinya belum memunculkan nama baru. Yang beredar masih nama-nama mainstream,” demikian msm Leak pada saya, 25 Juli 2018.
Lho, kok? Padahal berdasar pengamatan Kompasiana dewasa ini lebih dari 5.000 puisi setiap hari beredar di laman gawai (Isson Khairul pada Diskusi Sastra di Jakarta, 7 Juli 2018). Masak dari luahan populasi itu belum muncul nama penyair/sastrawan baru selain mereka yang sebelum era gawai telah bergelimang pada penulisan sastra? Agaknya perlu diurai apa itu yang dimaksud dengan sastra dan puisi sastrawi.
Arti harafiah sastra adalah huruf (Sapardi Djoko Damono), kemudian berkembang menjadi tulisan. Sejak aksara pertama ditemukan, huruf baji, oleh suku Akadia bangsa Sumeria di lembah Mesopotamia lebih dari 5.000 tahun silam, para penulis mendapatkan martabat yang terhormat di tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, pesan-pesan kebijakan dalam kehidupan, utama lafal-lafal ritual, dituliskan dengan berbagai varian, yang tertanda sebagai susastra, sastra indah.
Keindahan di sini bukanlah bentuk kaligarafis, melainkan bobot pesan yang disandangnya. Isinya. Susastra inilah yang kemudian kita kenal sebagai sastra sedang sastra lama disebut nonsastra.
Seirama perjalanan waktu dan peradaban sastra (susastra) tidak terbatas pada pesan tentang pendangan hidup, nlai-nilai kerohaian sesuai ajaran religi, melainkan mengalami pergeseran dengan mewadahi kebutuhan tentang hiburan. Sehingga di samping sastra tuntunan yang bermulti tafsir dan membuka cakrawala pandang lebih luas (interpretatif literature) ada juga sastra tontonan yang menghibur (escape literature). Negara tak mampu membendung arus
Kini muncul sastra gawai (cyber literature). Sebagaimana karakter gawai yang memiliki kebebasan tanpa batas, bahkan menurut Kenichi Ohmae bahwa pada dunia tanpa batas dewasa ini regulasi negara tak mampu membendung arus kebebasan publik konsumen dalam memilih selera barang dan jasa (juga jasa hiburan di gawai tentunya), maka sastra gawai menjadi pilihan dan alternatif sastra masa depan. Meski demikian, publik (yang sadar dan peduli) akan memberikan batas pembeda antara literasi gawai yang sastrawi dan nonsastrawi, pun untuk status yang berpola puisi.
Sejatinya, puisi adalah inti dari sastra. Kenapa? Puisi, puitika, artinya indah. Sesuatu yang indah adalah puisi. Alam yang indah natural puitika. Perilaku yang indah adalah perilaku puitis. Begitu pun zat yang memiliki sifat-sifat keindahan bisa disebut puisi (bukan dalam arti sastra). Lalu, apakah indah itu? Yang ritmis, kompositif, harmonis. Yang selaras, serasi dan seimbang. Hal itu hanya mungkin bila semua unsur-unsur dan partikel-poartikelnya dalam posisi yang presisi.
Nah, sampai di sini, untuk mendefinisikan persisi dalam estetika, tidak bisa secara matematis eksakta, sebab kaitannya dengan rasa dan jiwa. Jenis lain dari karya sastra (cerpen, novel, naskah drama, esai) bagamanapun juga memiliki kandungan puitika, maka puisilah sebagai inti dari sastra.
Memang, dewasa ini tengah terjadi pembauran, terutama di laman gawai yang diisi oleh peliterasi dari latar belakang yang heterogen. Tidak masalah. Sastra gawai hanya sebagian kecil dari manifestasi budaya abad now pada kultur postmodern di mana para pakar dunia menyebutnya sebagai era hyper reality, zaman yang melopati kenyataan.
Terjadilah pembauran antara impian dan kenyataan. Di kehidupan sosial sudah lama terjadi. Semisal seorang yang secara riil dalam penghasilannya masih belum layak memiliki mobil, rumah, toh nyatanya bisa amendapatkan kredit untuk mencapai keinginannya tersebut. Begitu pun dalam sastra.
Mereka yang belum faham puisi dan laku puisi bisa saja mengklaim diri sebagai penyair karena rajin menulis puisi (menurutnya) di laman gawai. Kita harus menyadari realitas zaman. Cobalah kita kutip beberapa contoh pernyataan dari postingan sobat Muklis di atas, yang menunjukkan heterogenitas sastra gawai, sebagai berikut:
Banyak kusayangkan, para aktor penulis sastra dunia maya mencemari sastra dengan berbagai cara. Kadang asal nulis (Imam Pujo Arum Joyo Kusumo).
Bagiku puisi adalah rangkuman kata hati yang dituangkan ke dalam tulisan, dan di situ dituntut kejujuran. Puisi yang lahir dari beronani jiwa, maka hasilnya pun hanya berupa khayalan-khayalan belaka (Oechocks).
Aku tak peduli dengan apa yang dikatakan orang atau apa yang dikatakan dunia maya tentang puisi... bagiku menulis adalah sebuah pemenuhan rasa asa bahkan birahi yang tumpah ruah di ruang kepalaku... aku mulai merasakan bahwa menulis puisi adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk mengatasi stress yang teramat sangat (Drs. Mustahari Sembirng).
Saya suka menulis menuangkan apa yang saya lihat, pengalaman pribadi dan curhatan orang lain hingga menjadi pembunuh kejenuhan di sela-sela kesibukan, tanpa mengacu pantas tidaknya, semoga tak ada yang merasa dirugikan (Karan Figo).
Meski tak mengerti tentang puisi namun menulis ungkapan isi hati di dumai membuat nyaman di hati (Pipit Dan Balada Elang). Apa layak disebut seni pabila mengkuti aturan, terikat oleh bentuk-bentuk tertentu?
Ini bukan hanya berlaku untuk puisi saja tapi juga seni-seni yang lain. Bagaimana seni mampu berkembang jika tangan maupun inspirasi kita terborgol? Maka jadilah kita pribadi seniman yang bukan ciri khas diri, jadlah kita plagiat, kemonotonan. Kalau mau nyebur sumur, nyebur berjamaah (Damar Alehendra).
Wajarlah kalau puisi atau pun sastra di sosmed tidak sesuai pakem atau aturan yang ada dan dipandang sebelah mata, atau pun cibiran dari para pujangga. Sebab, kebanyakan penulis sastra di sosmed tidak memelajari secara dalam (rata-rata hanya pengetahuan di bangku sekolah yang hanya pengenalan saja) dari SD sampai SLTA, semua hanya pengenalan sastra yang kapasitas pembelajarannya terbatas. Seperti saya, tidak tahu apa-apa, hanya berdasar naluri menuliskan. Maka aku tak peduli, tiap postinganku dianggap ada atau tidak ada, itulah karyaku (J Sumarto).
Di samping tentang kebebasan penulisan puisi yang disadari tanpa berbekal pengetahuan sastra (dan keengganan belajar), juga ada komentar tentang kritik. Sebab dalam esai itu Muklis menulis sebagai berikut: “Uniknya hampir semua komentar maupun kritikan selalu mengacu pada konsep keilmuan yang bersifat subjektif.
Amatan penulis, banyak dari kritikus dan komentar menginginkan cara dan aturan menulis puisi mengikuti gaya dia. Dengan kata lain, jika ada puisi yang diposting, tidak sesuai dengan karakternya langsung dinasehati dengan bahasa yang santun agar mengekor di belakangnya.” Kalaimat itu sertamerta menghadirkan komen-komen sebagai berikut:
Bagi setingkat prof atau pengaji lainnya memandang puisi dari segi bentuk dan gaya bahasa hanyalah upaya kemunduran dialektika. Periodesasi sastra Indonesia semakin jauh. Dialektika bentuk puisi sudah dimulai sejak era Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, hingga modern sampai postmo, apakah masih perlu? Saya rasa harus dikikis. Mulailah mengenali banyak kajian kesusastraan dari sosiologi, psiko, antro, ekolog, hingga mungkin astronom. Pengetahuan dan wacana yang dimiliki penyair akan membentuk struktur puisi dengan sendirinya (Toriq Fahmi).
Rasa tidak bisa dikritik, memangnya kita mau rasa kita terhadap pasangan hidup kita dikririk? (Sutiyoso Wijanarko).Harusnya krirtikus itu bukan penyair dan sebenar-benarnya kritkus itu ya insan penikmat puisi. Dikritik seperti apa pun jika satu puisi bisa tinggal di banyak kepala lebih lama, itu puisi yang memang mengena. Jadi puisi itu ungkapan batin manusia, bukan kitab suci, aneh rasanya jika puisi dituntut sempurna oleh seorang kritikus, apalagi tolok ukurnya juga sama, perasaan pengritik juga (Jangkung Asmoro).
Puisi memang seni. Tetapi seni bahasa. Dan bahasa itu harus dikritik. Jika tidak maka akan salah. Bagaimana jika kritikus sastra itu juga penulis sastra seperti penyair? Justru inilah yang bagus. Sebagai jadi balance. Antara pengalaman, teorti dan praktek. Kalau ada lihat komen orang di komentar maya tentang kritik dan celaan maka itu bukan termasuk kritik sastra. Itu komen sanggahan saja.
Kritik sastra itu lengkap. Ada keilmuannya. Kritik itu menimbang baik dan buruk dari berbagai suut pandang akademisi. Kebanyakan pemula tidak bisa membedakan ini. Celaan atau komen yang mengatakan puisi buruk malah dikatakan kritik sastra. Secara umum kritik sastra terbagi dua: 1. Kritik akademis (biasanya ada di kampus), 2. Kritik nonakademis (ini bisa dapat di kolom opini, maya, dst., seperti yang kami tulis). Kritik akdemi itu lebih mutlak.
Jika diperdebatkan ya harus sesuai keilmuan dan teori yang dibahas. Kritikus sastra memang tidak wajib sebagai pemain yang hebat, seperti jadi penyair atau novelis hebat. Seperti contoh: HB Jassin. Tetapi beliau juga pandai menulis sastra seerti puisi. Kalau ada kritkus sastra bisa sebagai pemain mahir malah makin lengkap dan baik, contohnya Sapardi Djoko Damono (Indra Intisa).
Lucunya kalau sesama penulis dikritisi sedikit dan diberi masukan malah mengatakan menjastis puisi si A harus bagus seperti yang memberi masukan, itu suatu bentuk patonah atau fitnah, yang sebetulnya ia ingin mengalihkan pembicaraan atau mau menggiring pembaca bahwa yang mengritisi dan membari masukan salah besar. Aneh dan lucu (Eko Windarto).
Anekaopini yang tertuang pada komen-komen di atas menunjukkan heterogenitas peliterasi gawai baik dari segi pengetahuan maupun laku sastra. Tak apa-apa. Ini memang realitas zaman now. Kembali kepada kesadarpedulian masing-masing pribadi, sebab seni berangkat dari jatidiri setiap insan yang berdedikasi dan mandiri. Terus terang, yang menggembirakan (dan saya optimis karena berpikir positif) bahwa media gawai telah merebak-kembangkan apresiasi sastra dan puisi.
Pada tahun 1970-1980 Pemda DKI mendanai projek aprsiasi seni dan saastra di kalangan remaja yang dioperasionalkan di lima Gelanggang Remaja Jakarta, dan saya sebagai kordinator sastra pada awal proyek tersebut.
Kini pada era gawai, tanpa dikeluarkan dana sepser pun oleh pemerintah, minat sastra di kalangan remaja kian merebak. Sayangnya tidak disertai pembinaan. Memang, kita belum memiliki semacam pola dasar pembinaan dan pengembangan sastra. Barangkali, inilah yang menjadikan kebebalan sastra kita, seperti diisyaratkan sastrawan Sapardi Djoko Damono. Diperlukan keberpihakan pada sastra gawai. Salam leterasi.
Penulis adalah Esais Nasional berdomisili di Bogor

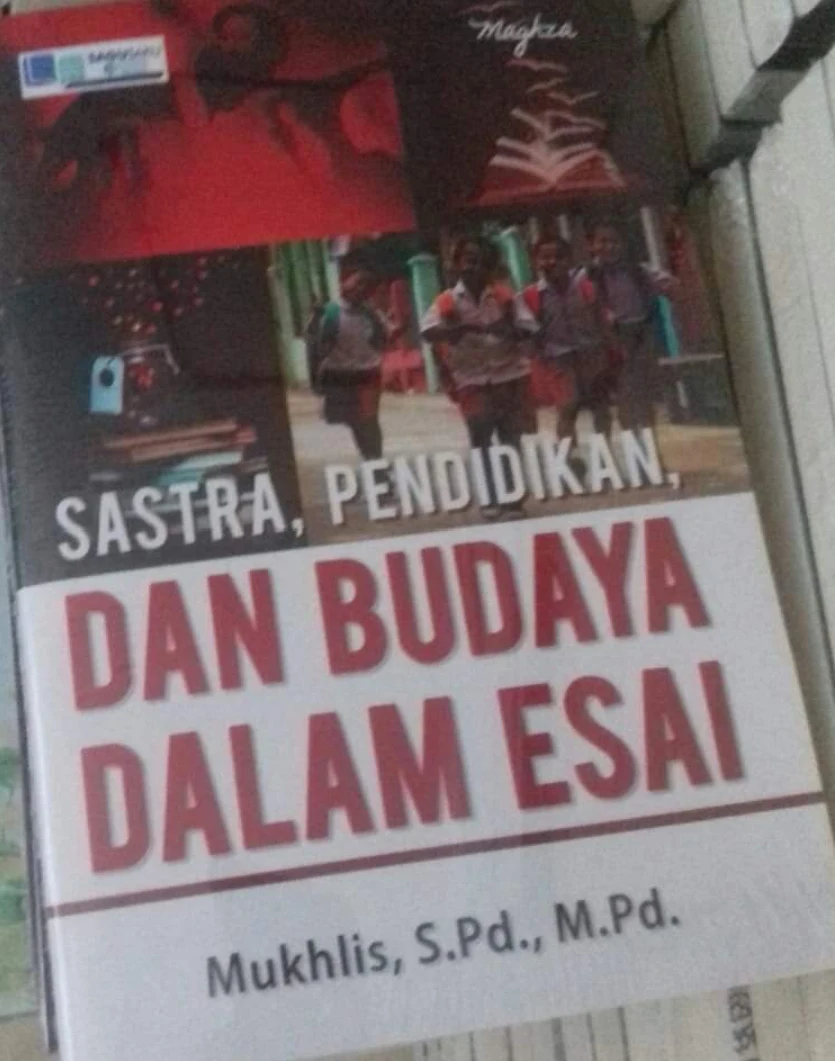





0 Komentar